Skripsi Krispi
Yang berlalu biar berlalu
Apa enaknya dibalut sendu?
Yang berlalu biarlah terasa kelu
Orang bilang tangis membantu,
itu tak selalu.
Alunan lagu berjudul "Yang Berlalu Biar Berlalu" oleh Rasukma sayup terdengar di kepala.
Tiba-tiba muncul tanya yang diiringi lamunan,
"Tahun ini, sudah berapa kali aku terburu pilu? Berapa kali tangis itu bergema? Berapa lama sampai kemudian mereda?"
Pertanyaan yang tiba-tiba muncul disaat gue tengah melamun dalam kamar kost ditemani rintik hujan yang gak jelas kapan datangnya.
Jatinangor dan Bandung seperti punya dua musim yang berbeda dan kedua musimnya bisa dirasakan secara bersamaan saat berpergian dari Jatinangor ke Bandung ataupun sebaliknya.
Kembali ke pertanyaan beruntun yang tiba-tiba datang, gue jadi kembali merenung sejenak,
Kenapa banyak hal yang dar der dor dalam hidup gue di tahun ini?
Entah dalam konteks senang atau susah, tapi yang jelas semuanya datang terlalu tiba-tiba.
Gue tau dunia emang brengsek,
tapi tolong jangan paksa gue untuk menikmatinya.
Sebagai mahasiswa semester 7, gue dihantui dengan apa yang orang-orang sebut dengan skripsi.
Mimpi buruk semua mahasiswa.
Entahlah gue harus marah sama siapa, tapi yang jelas, gue mau gak mau harus menyusunnya.
Sejujurnya, gue gak pernah punya masalah sama menulis. Gue suka dan terbiasa dengan hal itu. Tapi, entah kenapa skripsi gak sama dengan gue nulis di blog maupun me-review film. Skripsi adalah hal serius yang nantinya (semoga) bisa bermanfaat entah dalam masyarakat atau dunia akademik. Untuk gue yang alergi dengan keseriusan, skripsi ini kembali menyisakan banyak tanya mendalam.
"Ini gue harus ngapain? Ini mulainya dari mana? Dari 0, Mas?"
Bingung. Semua orang bingung.
Gak ada kelas menulis skripsi di mata kuliah kampus, gak ada les skripsi di dunia ini, dan gak ada yang ngasih tau do and don'ts dalam mengerjakan skripsi kayak panduan kalau mau nonton konser. Jadi, panduan gue dalam menyusun skripsi ya pakai panduan do and don'ts di konser-konser. Kayak ga boleh ngerokok, no drugs & alcohol, dan dilarang moshing pas denger lagu Tulus.
Tapi satu do yang paling gue ingat dan tersimpan dalam lobus temporal gue, yang sebenarnya gak hanya berlaku untuk skripsi aja, tapi juga dalam memilih jurusan, pekerjaan, atau simpenan (mau nabung di bank mana, maksudnya).
"Kalau mau nyusun skripsi, pilih topik yang lo suka, yang bikin lo semangat ngerjainnya dan lo gak bakalan putus asa di tengah jalan".
Bagai petuah dari Mpu Tantular, gue memegang nasihat itu erat-erat.
Gue gak mau mengecewakan Mpu Tantular atau Mpu Lela, emaknya si Doel anak sekolahan (iye tau itu Mpok).
Maka, satu hal yang terlintas di kepala saat itu adalah, buku.
Sebetulnya, buku bukan hanya hobi, tapi juga hidup gue.
Kedengarannya lebay, tapi begitulah adanya.
Dari kecil, gue berteman dengan kata. Bicara bukanlah hal yang jadi kebiasaan. Sedari dulu, lidah gue rasanya kaku dan kelu walau hanya sekadar untuk menumpahkan apa yang gue rasa. Apa yang keluar dari mulut gue saat itu adalah sewajarnya manusia berkeinginan (makan, haus, ngantuk), sedangkan apa yang gue rasa, entah itu marah, sedih, atau kecewa, semuanya terpendam rapat di dalam diri gue. Makanya, gue terus membaca buku supaya gue bisa memahami apa yang gue rasakan dari sudut pandang orang lain sehingga gue dengan mudahnya mengangguk kencang kalau-kalau ada kalimat dalam sebuah buku yang mewakili perasaan gue kala itu.
Tapi,
"Gue kan anak Hubungan Internasional, bukan Sastra. Kalau gue bahas buku, apa ngaruhnya buat dunia internasional saat ini? Apa sastra bisa meredam konflik? Tulisan bisa apa? Gerak juga engga, bunyi juga engga, udahlah jangan macem-macem. Konflik banyak, negara di dunia juga banyak, ngapain sih lo nyari yang di luar ranah lo lagi?" Pikir gue kala itu.
Pikiran ini jelas didukung oleh teman-teman dekat gue yang selalu mengingatkan gue akan,
"Udahlah, Pit. Skripsi tuh gak harus merubah dunia, kok. Kita baru S1. Tujuan kita kan biar lulus cepet atau tepat waktu, pikirin juga itu." Ucap Wianda, kala Gue, Brian, dan Thya sedang skripsian bersama di Tomoro. Kala itu, hanya gue yang belum dapat judul skripsi. Di saat mereka sudah menggarap bab 1, gue baru memulai main The Sims day 1.
Gue udah kepikiran berbagai macam judul sebetulnya yang kemudian gue diskusikan bersama mereka, tapi semuanya ada di ranah sastra. Misalnya, waktu itu gue lagi baca bukunya El Señor Presidente karya Miguel Ángel Asturias. Sebuah novel fiksi yang membahas mengenai kediktatoran dan politik kotor yang dilakukan oleh Tuan Presiden. Atau waktu gue tau ada novel The Handmaid's Tale yang membahas mengenai distopia dan kehancuran negara Amerika karena adanya krisis fertilitas perempuan yang memaksa perempuan subur untuk melahirkan anak-anak dari penguasa atau elit global, maka gue berpikir,
"Feminis di luar sana pasti marah, nih. Mary Wollstonecraft juga pasti gak suka."
Tapi kemudian gue urungkan karena waktu itu gue bertemu Rivandi, teman sejurusan gue yang mau membahas sastra juga pada topik skripsinya, namun dia akhirnya mengurungkan niatnya karena katanya dosen pembimbing yang selinier dengan sastra di HI sudah tidak di sana lagi.
Yah, ini sih gila.
Gue harus bahas apa kalau begitu?
Akhirnya gue menyerah dan pergi ke Pak Anton. Pemilik Perpustakaan Batu Api.
"Pak, saran topik skripsi yang HI, dong." Ucap gue dengan memasang tampang memelas.
"Oh ada nih, migrasi." Balas Pak Anton dengan entengnya.
Mata gue langsung terbelalak saat Pak Anton bilang begitu.
"Migrasi burung. Kan pindah-pindah negara tuh, kurang HI apa coba?"
DUAR! Ekspektasi gue runtuh. Maksud gue, iya sih, burung pindah negara buat bermigrasi, tapi kan gue bukan lagi neliti 'kira-kira burung keluar masuk perbatasan negara pakai paspor dan visa ga ya?' Dan satu lagi, gue juga bukan Nat Geo. Akhirnya gue kembali pulang dengan tangan kosong berbekal humor migrasi burung yang masih akrab di telinga gue sampai saat ini.
Sementara tekanan terus berdatangan. Ditambah saat itu Wianda dan Thya bilang,
"Pokoknya, bimbingan besok udah harus ada topik. Emang lo ga sayang, sekali nongkrong ngabisin duit tapi gak ngehasilin apa-apa?"
Benar juga. Jadi di malam itu, gue membuat dua draft skripsi.
Satu mengenai migrasi (bukan burung) pekerja perempuan di Asia Tenggara dan satu lagi soal buku El Señor Presidente.
Sementara Wianda, Brian, dan Thya menonton The Heretic tanpa gue, ya karena gue udah nonton sendiri juga sih, jadi gak masalah.
Gue membuat dua draft tersebut dengan harapan dosen pembimbing gue bisa menentukan apa yang sekiranya cocok dan mungkin untuk gue teliti. Jelas ada setitik harapan terselip supaya dosen pembimbing gue lebih memilih topik dan judul yang sastra abis dibandingkan migrasi-migrasi itu.
Judul siap, das sollen dan das sein siap (gampangnya fakta nyata di lapangan dan idealnya di lapangan kayak gimana), latar belakang aman. Maka gue siap menemui dosen pembimbing gue dengan seperangkat judul aneh di tangan. Let's go!
Keesokan paginya, gue terpikirkan satu hal. Belajar dari pengajuan topik sebelumnya, terang saja kalimat "Kamu anak HI apa anak Sastra, sih, Pit?" keluar dari mulut dosen gue dan terus bergema di kepala.
Gue yang tadinya krisis identitas sekarang berusaha untuk mencari argumentasi mengenai di mana HI-nya supaya ga jadi mahasiswa HI yang murtad.
Kalau topik yang migrasi jelas HI, tapi yang sastra? Maka gue mencoba memikirkan situasi dan kondisi apa yang memungkinkan untuk sebuah karya sastra berada dalam ruang lingkup Hubungan Internasional (iya gue tau ini gila).
flashback on:
Saat itu, gue berada di Bandung setelah melakukan tahap lanjutan untuk volunteer TedX. Sepulang dari sana, gue menghampiri teman gue, Putu, yang sedang membuat project untuk tema PKM-nya. Rencananya juga, gue akan melukis untuk project tersebut. Tapi naas, gue datang terlambat dan gue gagal melukis. Tapi karena sudah datang, jadi gue putuskan untuk bersosialisasi dengan anak-anak Sastra Inggris. Ada Fefe, adik tingkat gue di Radio Unpad yang menyambut gue dengan ceria kala itu.
"KAK IPIT! WIIIH SIAP NGELUKIS NIH! TAPI KITA UDAH SELESAI KAK!" Sambut Fefe, hangat.
"Yah, Fe, gue kayaknya salah kostum ya ke sini?" Bisik gue ke Fefe karena saat itu anak-anak Sastra Inggris menggunakan pakaian yang benar-benar senyamannya dengan paduan warna hitam-hitam sementara gue bak putri kerajaan dengan rok coklat tua, cardigan coklat muda, dan kemeja putih di dalamnya. Tidak menggambarkan seniman sama sekali. Ya abis, gimana dong? Gue harus datang ke acara formal dulu sebelumnya, masa pakai baju seadanya?
"Eh, gak apa-apa, Kak. Gak bakalan ada yang notice juga. Anyway, itu Pak Ari. Kepala Prodi Sastra Inggris. Lo tau lah hehe." Fefe bercerita dengan sumringah karena memang betul, topik soal Pak Ari as dosen nyentrik di FIB sudah menjadi makanan gue sehari-hari kalau gue sedang nongkrong di radio. Biasanya, kami membicarakan beliau dengan Brian dan Fefe sebagai anak sasing-nya langsung.
Gak pakai basa basi, Fefe langsung memperkenalkan gue pada Pak Ari.
"Pak, ini Ipit HI, tadinya mau ikut ngelukis, masih bisa gak, Pak?" Tanya Fefe.
"Aduh, udah selesai. Kalau ngelukis sekarang nanti gak kerasa feel-nya." Ucap Pak Ari yang sibuk menggariskan pensilnya di atas kain kanvas lebar karya anak-anak sasing.
"Gak apa-apa, Pak. Saya ke sini cuma mau ketemu Putu sama Fefe, kok." Balas gue.
"Kamu Ipit HI? Saya kira Sastra Indonesia (Sasindo). Soalnya waktu itu ada juga anak Sasindo yang chat saya." Tanya Pak Ari sekaligus menjelaskan.
Gue jadi ingat beberapa hari sebelumnya saat gue baru selesai mengisi form untuk mengikuti kegiatan ini, lalu tiba-tiba Putu mengirimkan pesan,
"Pit, lo anak Sasindo ya? Atau dulu lo anak Sasindo?"
Di situ gue bingung. Perasaan, gue ketemu Putu di kelas gender yang mana itu adalah mata kuliah HI. Dia tau dong, harusnya gue anak HI? Tapi kenapa tiba-tiba gue dituduh Sasindo?
Sampai akhirnya ketika Pak Ari berkata begitu, gue jadi ngerti kenapa Putu bertanya hal serupa.
Kembali ke Pak Ari. Ketika dia tau gue anak HI dia berkata dengan santai,
"Anak HI sok pinter, ya?" Tanya Pak Ari.
Ini yang gue tunggu.
"Mungkin? Emang kenapa gitu, Pak?" Balas gue dengan nada becanda.
"Soalnya anak HI yang saya temuin suka sok pinter" Jawabnya dengan nada becanda juga.
Gue sudah tau dan memaklumi hal ini. Fefe berbisik setelahnya,
"Emang suka begitu, Kak, gak cuma HI, semua jurusan pasti dia roasting. Kita anak sasing-nya aja di roasting."
Gue hanya tertawa setelahnya.
"Pak, Kak Ipit suka baca buku, loh." Pantik Fefe lagi
"Oh iya? Baca buku apa?" Tanya Pak Ari yang kembali sibuk menggaris.
"Sastra Inggris klasik sih, Pak. Kayak T. Elliot, Fitzgerald, Jane Auesten. Nah, Pak Ari ada rekomendasi ga selain itu?"
"Sherlock Holmes?" Ucapnya sembari menengok karena posisinya saat itu tengah memunggungi gue sambil menggaris.
"Wah itu sih udah tamat." Kata gue dengan bangga.
"Suruh masuk kelas literature film, Fe." Ucap Pak Ari ke Fefe.
"Apaan itu?" Tanya gue, penasaran.
"Kelas semester genap, Kak. Pak Ari suka banget Sherlock Holmes dan biasanya beliau bahas itu di kelasnya" Kata Fefe, menerangkan.
"Aduh, sulit deh, Pak, kalau harus nambah kelas. Tapiii, saya mau bahas sastra di skripsi saya. Kira-kira possible ga, Pak?" Tanya gue, penasaran.
"Itu sih kamu nyari penyakit."
"Kenapa emang, Pak?"
"Zaman sekarang, ngapain coba masih pakai konsep negara-negaraan? Kamu pikir sastra bisa digabungin sama teori-teori HI? Susah lah."
Semangat gue sejujurnya hampir patah. Memang benar kata Pak Ari, gue seperti sedang menyeburkan diri ke pasir hisap. Tapi entah kenapa, ada segelintir hal di kepala gue yang bikin gue gak setuju sama statement Pak Ari.
Hingga akhirnya, gue pamit pulang, tapi sebelum itu karena tau Pak Ari seorang penulis dan katanya peluncuran bukunya akan diadakan dalam satu bulan lagi, maka gue meminta dia untuk,
"Biar saya pulang gak tangan kosong, kasih dong, satu quotes yang paling 'nendang' di buku Pak Ari."
Lalu bak Shakespeare, Pak Ari pun berkata,
"Kalau puisi itu luapan jiwa, bisa kujual sajakku ke petugas tinja."
"HAHAHAHHAHAHHA" Tawa gue dan Fefe bersamaan.
flashback off:
Di tengah keburu-buruan yang melanda, gue langsung datang ke rektorat untuk bimbingan walau untungnya, Kayla, teman satu bimbingan gue belum selesai berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi, gue menunggu di sofa dan tiba-tiba ada Zaki,
"Pit! Udah ketemu topik skripsimu mau apa?" Tanya Zaki dengan bersemangat. Dia udah dapat judul duluan dari beberapa bulan yang lalu.
"Belum, Zak. Tapi yang paling baru, kayaknya gue mau bahas migrasi deh. Soalnya kemarin sempat jadi tugas gue di Studi Asean." Balas gue sembari membuka laptop.
"Coba liat" Tagih Zaki, yang membuat gue menunjukan laptop gue di tengah gue yang sibuk cari argumentasi kalau sastra juga masuk ranah HI.
"Oh kalau ini sih sama kayak aku!" Ucap Zaki, setelah membaca draft tersebut.
"Yah, sama dong kalau begitu? Gue cari yang lain deh." Ucap gue pasrah.
"Eh! Sama tapi kan arah penelitiannya beda. Kamu pakai teori feminisme kalau aku bukan. Tapi nanti pas nyari datanya siapa tau bareng blablablabla..."
Karena gue masih sibuk mencari argumentasi, gue tidak mengindahkan perkataan Zaki dan sampai akhirnya,
"Zak, bisa diem dulu gak? Sorry ya, tapi gue lagi buat draft ketiga."
"HAH TIGA?"
"Iya, bentar ya." Ucap gue yang kembali menyisakan keheningan diantara kami berdua. Akhirnya Zaki mengobrol dengan yang lain sementara gue sibuk melihat di Google dan ada sesuatu yang menarik mata gue.
"Apaan nih? Franklin Book Programs?" Tanya gue dalam hati.
Gue pun mencari di search engine dengan keyword serupa.
Ada satu skripsi anak sejarah Universitas Gajah Mada yang meneliti hal tersebut. Gue kembali mencari artikel jurnal lain, tapi naas, artikel-artikel tersebut kebanyakan dalam bahasa Inggris. Hanya satu yang berasal dari bahasa Indonesia, ya skripsi anak UGM itu (Akhirnya gue dibantu Arsya untuk mengakses skripsi ini).
Hingga akhirnya, seperti dapat ilham, semburat cahaya tiba-tiba menyinari laptop gue (lebay), gue langsung mengetikan judul ketiga dalam draft yang gue buat. Tanpa ada latar belakang atau research gap, tok, yang gue ketikan hanya sebuah judul dalam Google Docs.
Ga lama setelah itu, giliran gue yang bimbingan.
"Saya udah baca yang kamu kirim semalam di Google Form, Pit. Sastra lagi?" Ucap Bu Anggi masih dengan heran.
"Aduh, Bu, tahan dulu ada satu lagi. Tapi karena semalem cuma bisa saya upload satu, jadi satu lagi saya tunjukin sekarang aja ya." Gue spontan langsung membuka laptop dan membiarkan Bu Anggi, dosen pembimbing gue membaca draft kedua gue terkait migrasi.
"HAH? MIGRASI? UDAH MIGRASI FEMINISME LAGI? ADUH!" Bingung Teh Anggi saat itu. Ibaratnya gue beneran banting setir dan bantingnya sampai nabrak pohon .
"HAHAHHAHAHAHA!" Tawa teman-teman lain yang ada di belakang gue.
"TAHAN DULU, BU, ADA SATU LAGI! Tapi, saya baru banget liat ini. Pas banget waktu saya barusan ngobrol sama Zaki tadi. Jadi, baru ada judul doang" Ujar gue, pesimis.
"Ya udah mana?" Tagih Bu Anggi.
Gue akhirnya menunjukan tab baru yang sempat gue tutup karena malu. Setelahnya, gue kembali menjelaskan sedikit apa yang baru saja gue baca.
"Wah, menarik sih ini. Ya udahlah, Pit. Ini aja."
"HAH? SERIUS TEH?"
"Iya. Ini soal containment anti komunisme-nya AS kan? Nah kalau ini ada HI-nya. Soalnya Franklin Book Progams ini jatuhnya kebijakan Amerika waktu Perang Dingin. Ya udahlah, buat bab 1 nya" Ucap Teh Anggi enteng.
"Asiiik! Siap Teh." Gue tersenyum sumringah sembari mematikan laptop dan ingin segera beranjak pergi untuk mencari tahu apa Franklin Book Progams ini.
"Udah ya, Pit. Ini aja, jangan ganti yang lain." Ucap Bu Anggi, mengingatkan. Khawatir gue berubah pikiran di tengah jalan.
"Pasti, Teh. Makasih ya, Teh Anggi!" Gue akhirnya meninggalkan rektorat dengan gembira. Menyisakan teman-teman gue yang berkata,
"Udah, Pit? Cepet amat?"
Gak bisa gue pungkiri bahwa itu adalah bimbingan tercepat kilat yang pernah gue lakukan.
Tujuan gue setelahnya adalah Batu Api. Perpustakaan kecil yang dimiliki oleh Pak Anton dan Teh Arum.
Buat gue, mereka udah seperti orang tua gue di Jatinangor. Kalau sehabis kelas atau mau baca buku, biasanya gue akan melipir sebentar dan menghabiskan waktu untuk baca atau sekadar ngobrol ngalor ngidul sama Pak Anton.
Sesampainya di Batu Api, gue pasti akan menabrak sebuah lonceng yang ditempelkan di tengah pintu sehingga kedatangan setiap tamunya akan diketahui oleh Pak Anton yang tengah duduk di dalam.
Baru sampai di pintu, Pak Anton sudah melihat gue senyum sumringah,
"Pak. Saya udah dapet topik skripsi. Bapak tau Franklin Book Programs, gak?"
"Hah? Apaan?"
Gue bingung. Biasanya kalau gue menyebut apapun yang keluar dari mulut gue, entah film, buku, atau artis, Pak Anton pasti tau. Kenapa sekarang dia ga tau? Atau pura-pura gak tau?
"Serius, Pak? Program kerja Amerika waktu Perang Dingin buat publikasi buku terjemahan bahasa Inggris ke negara-negara berkembang."
"Ah baru denger saya." Ucap Pak Anton "Tadi apa namanya? Franklin Book Programs?"
"Iya, Pak, nih beberapa bukunya." Gue pun akhirnya memberikan list-list buku Franklin Book Programs ke Pak Anton melalui website Franklin Book Programs-nya langsung.
"1... 2... 3... 10" Kata Pak Anton, seperti menghitung buku-buku yang kemungkinan ada
"HAH? SERIUS PAK ADA?" Ucap gue dengan nada terkejut. Jelas saja, buku-buku tersebut pasti sangat langka. Terhitung dari usia cetaknya di tahun 1960-an yang terpaut 65 tahun dari tahun 2025. Belum lagi dengan adanya buku-buku yang gagal cetak. Adanya buku-buku tersebut yang kemudian menjadi sumber primer gue, membuat gue yakin bahwa penelitian gue bisa jadi mungkin. Tapi keraguan gue muncul, gue harus wawancara siapa?
Hingga akhirnya gue pulang dengan tangan kosong sembari membawa buku Wijaya Herlambang yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film.
Setelah gue baca buku tersebut, gue menyadari satu hal,
Congress for Cultural Freedom ternyata bagian dari strategi penerbitan di era Perang Dingin. Sama kayak Franklin Book Programs.
Damn, suatu kebaruan.
Beberapa hari setelahnya, gue kembali ke Pak Anton. Belum berapa lama, dia sudah memanggil gue dengan sebutan Franklin.
"Tuh, si Franklin dateng." Unjuknya ke gue saat ada seorang anak lain yang tengah ngobrol di depannya. Tanpa mempedulikan orang tersebut, gue langsung berkata,
"Gak Franklin lagi, Pak. Sekarang tambah Congress for Cultural Freedom. Pak Anton tau sesuatu gak tentang itu?"
Lagi-lagi gue mendapatkan jawaban yang tidak diharapkan,
"Hah, apaan itu? Saya baru denger"
"Pak, ayolah. Ini pernah dibahas Wijaya Herlambang dibuku yang kemarin saya pinjem. Pak Anton pasti tau. Tapi ya, Pak. Saya harus wawancara siapa ya? Bingung." Rayu gue.
Hingga hening membawa kecanggungan antara kami berdua. Tiba-tiba Pak Anton berkata,
"Namanya Kelana Wisnu. Cari coba di Instagram.
"Hah, siapa?"
"Coba cek aja, dia suka bahas soal Perang Dingin, CIA, sama Amerika"
Akhirnya, gue mencoba menghubungi orang yang dimaksud. Hampir di accept lama, sampai akhirnya gue berhasil di follback dan gue mengirimkan pesan ke Kak Wisnu. Kami sudah sempat chat-an, tapi belum ada kesempatan untuk bisa ngobrol langsung hingga hari ini. (Kalau Kak Wisnu baca blog ini, tolong sabar-sabar ya, Kak. Nanti bakalan aku hubungin lagi, kok. Hehe)
Setelah itu, gue merasa mantap.
Gue akan membawa Franklin Book Programs dan Congress for Cultural Freedom ini ke dalam skripsi gue. Gak ada yang bisa menghalangi semangat gue. Sekelebat info yang gue tahu juga, ternyata Congress for Cultural Freedom ini menyuntikan dana ke majalah sastra paling berpengaruh di tahun tersebut yang bernama majalah Horison.
Hingga proses bimbingan terus berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
Satu yang tiba-tiba membuat gue bimbang di akhir,
"Ini udah HI belum ya?"
Sampai akhirnya, gue bertemu dosen penguji gue di Batu Api. Gue bertanya karena didorong oleh Pak Anton saat itu,
"Teh, kalau saya bahas Franklin Book Programs pakai teori postmodernisme gimana, nyambung ga ya kira-kira?"
"Aduh apa itu?"
Akhirnya gue menjelaskan walau saat itu gue belum yakin apa yang akan gue bahas.
"Saya gak tau sih, soalnya saya aja baru denger"
Waduh. Bahkan dosen penguji gue juga bingung.
Maka, gue mengulik banyak teori HI. Sebelum-sebelum ini, gue bahkan ga peduli sama teori-teori yang ada dalam HI. Entah sekarang gue kesambet apa sampai tiba-tiba baca teori Hegemoni-nya Gramsci di Tomoro, atau Power and Knowledge-nya Focault, termasuk teori Postmodernisme yang bahkan sampai sekarang gue gak ngerti-ngerti itu apaan. Sampai akhirnya gue mengukuhkan dan memantapkan diri kalau gue pakai teori Konstruktivisme.
Berangkat dari pikiran,
Oh, ide dan gagasan itu merupakan konstruk sosial. Dengan adanya buku-buku terjemahan dari FBP dan CCF, berarti Amerika ingin menanamkan ide dan gagasan liberalisme yang kala itu tengah digaung-gaungkan sebagai bentuk pembendungan ideologi komunisme di negara berkembang dengan media penerbitan buku.
Maka, gue dengan pede-nya menggunakan judul, teori, dan konsep yang gue bawa untuk Seminar Usulan Riset (SUR).
Sebetulnya gue gak pede. Banyak faktornya dan gak bisa gue jelaskan di sini. Tapi yang jelas, gue merasa topik gue ini sulit. Di dunia ini bahkan gak ada yang tau FBP dan CCF. Gimana gak gila?
Kegilaan ini dibarengi dengan keteguhan gue untuk tetap melanjutkan penelitiannya. Sampai akhirnya gue dengan pedenya daftar Seminar Usulan Riset itu. Gue bahkan sudah mengirimkan draft sur gue ke semua dosen penguji.
Tapi, di H-4 gue bertemu Kak Cantya dan Rahma untuk ngerjain persiapan SUR di Dunkin Donuts.
Kebetulan gue dan Rahma akan SUR berbarengan di tanggal yang sama dengan waktu yang berbeda. Rahma di jam 2 sementara gue di jam 10.30.
Saat Kak Cantya membaca draft gue, respon dia saat itu adalah ketawa.
Gimana engga, antara latar belakang, rumusan masalah, sampai ke bab terakhir ga nyambung semua.
Ada hal yang lebih parah dari ini, tapi akan gue keep demi nama baik dan reputasi gue yang gak seberapa ini.
Masalah lainnya adalah, gue udah nge-print out 6 filenya yang jelas udah merogoh kocek yang lumayan. Tapi, gue bersikukuh untuk merevisi habis semuanya dan mencetak ulang lagi. Gila.
Tau apa yang lebih gila? Gue cuma punya waktu kurang dari satu hari untuk merevisi semuanya.
Malamnya, Rahma, Kak Cantya, dan Thya menginap di rumah gue.
Gue pusing bukan main, tapi harus gue pendam untuk menghindari kepanikan berlebih. Gak enak dong, masa ada tamu gue bengong dan nangis? Maka, gue pamit ke mereka untuk tidur duluan setelah gue mengirimkan draft sur gue yang Brian minta untuk dia review besoknya.
Gue udah gak kuat.
Maka gue tertidur.
Pulas.
Sampai akhirnya saat pagi-pagi menjelang, gue melihat Rahma sedang duduk di atas meja menghadap ke jendela yang langsung menunjukan pemandangan Gunung Geulis yang tinggi menjulang dikelilingi dengan langit birunya.
Dia tiba-tiba berkata selepas gue keluar dari kamar mandi,
"Lo semalem kenapa?"
"Hah? Kenapa?"
"Lo muntah"
"MANA!?"
Gue beneran panik karena takutnya gue atau teman-teman meniduri atau bahkan membersihkan bekas muntahan gue sendiri kalau emang gue muntah. Masalahnya, gue gak ingat.
"Semalem lo muntah sampe gue pegangin" Ucap Thya dengan suara serak akibat baru bangun tidur.
"Terus gue muntah di mana?" Tanya gue panik.
"Di kamar mandi" Ucap Rahma.
"Beneran muntah?" Tanya gue lagi.
"Gak tau" Jawabnya.
Wah, gak beres.
Jam menunjukan pukul 9 pagi.
Kak Cantya, Rahma, dan Thya pergi pulang meninggalkan gue sendirian di kostan. Sejujurnya di saat mereka pergi, gue juga segera bergegas pergi ke Tomoro untuk merevisi dengan waktu maksimal sore itu. Menurut dosen pembimbing gue, hal itu dilakukan karena dosen penguji juga perlu membaca keseluruhan draft gue yang harus dikirim maksimal hari senin di jam kerja. Baik, gue sepakati hal tersebut.
Pun, dengan powerpoint yang juga harus dikirim sore itu juga.
Wah, gue gila. Setengah otak gue kayaknya agak geser dikit.
Belum lagi gue harus mengerjakan tugas kelompok mata kuliah penelitian kuantitatif kelompok yang deadline-nya hari itu juga di jam 23.59.
Maka, sesampainya gue di Tomoro, gue memesan satu buah kopi susu dan satu croissant karena belum sarapan. Setelahnya gue menangis.
Gue menangis karena ada tantangan di depan mata dan gue gak tau harus gimana.
Untungnya saat itu Tomoro sepi, kalau ramai mungkin gue udah dipuk-puk sama semua pengunjung di sana, kali.
Di tengah kesintingan itu, gue mencoba untuk mendistraksi pikiran gue dengan niat untuk mendengarkan musik.
TAPI TWS GUE KAN ILANG.
Sudah jatuh tertimpa teks.
Akhirnya gue jalan dari Tomoro yang letaknya di Ciseke ke Jalan Sayang dan membeli satu buah earphone seharga sepuluh ribu karena gue yakin tws gue gak hilang tapi ketinggalan di rumah.
Mereka berdua datang bersamaan dan langsung duduk di sayap kanan sementara gue di kiri.
Hingga akhirnya ketika gue menatap kaca yang menempel di samping mereka, Fay akhirnya sadar akan hadirnya gue dan langsung laporan ke Gri.
"Lah?" Ucap mereka.
Entah kenapa tiap liat muka mereka, gue bakalan ketawa karena kebayang muka mereka pas main kartu dan Fay kalah terus.
Gue kemudian menyebutkan kawan-kawan sekelompok gue.
"Lo dari kapan dateng?" Tanya gue sembari berjabat tangan dengan Rofi.
"Barusan, nih, lo dari kapan?" Tanya Rofi balik,
"Dari jam 9 gue di sini, belajar buat sempro." Balas gue yang diiringi semangat dari Rofi. Ia akhirnya pergi meninggalkan gue ke meja Fay dan Gri.
Saat waktu maghrib tiba, gue menitipkan barang-barang gue ke Rofi untuk beristirahat sejenak dan keluar sembari mencari angin segar.
Baliknya, gue lihat Rofi sudah duduk di meja gue. Gue kaget. Ngapain dia di situ?
"Biar makin aman, gue kan secmed (security medic) pormak (porang makrab)"
Oh, iya sih. Itu divisi dia. Tapi kan itu semester 1.
Akhirnya, gue kembali mengerjakan skripsi drunk text gue dan mengubahnya menjadi sober text. Tinggal sedikit lagi padahal janji gue pada dosbing untuk mengirimkannya sore. Tapi apa mau dikata? Gue harus membagi otak gue pada percabangan lain seperti ADKHI, Powerpoint presentasi, dan draft skripsi.
Di saat gue sudah selesai mengerjakan draft dengan terseok-seok, muncul Brian dengan wajah segarnya.
"Abis mandi lo ya?" Tanya gue.
"Engga" Sanggah Brian.
"Seger banget mukanya" Ucap Rofi.
Brian akhirnya mengambil posisi duduk di sebrang kanan gue karena di depan gue ada Rofi dan sebelah kanan gue ada Gri yang sibuk cerita mengenai kelompoknya yang kocak. Lalu langsung saja gue membuka percakapan,
"Lo udah baca draft tolol gue ya? Gimana menurut lo?" Tanya gue penasaran. Gue memang sudah mengirimkan draft skripsi versi mabuk itu malamnya.
"Gue gak bilang tolol sih karena gue ga ngerti topiknya, tapi pertanyaan gue, kenapa variabelnya 2?" Tanyanya, sembari duduk dan membuka laptop.
"Nah gini..."
Gue akhirnya menceritakan semuanya dan dia kembali mengangguk-angguk entah mengerti atau tidak, tapi gue gak peduli. Gue hanya bingung karena dikejar waktu.
Akhirnya Gri, Fay, dan Rofi pamit undur diri menyisakan gue dan Brian. Tapi Rofi balik lagi karena earphone-nya ternyata gak sengaja gue masukan ke dalam tas gue.
Setelah gue siap untuk tanya jawab, gue pun dengan setengah mantap berkata ke Brian,
"Bri, gue siap. Lo boleh tanya apa aja."
"Oke. Kenapa penelitian ini penting untuk diteliti?"
Belum apa-apa gue udah menyerah,
"BRIAAAN~"
Ucap gue hampir menangis.
Ketika gue tengah menenggelamkan wajah gue ke meja, sayup-sayup dengar Brian panik dan bilang,
"Pit, mau minum dulu engga?" Ucapnya pelan.
Gue hancur. Pertanyaan sesimpel itu aja gue gak bisa.
Hingga akhirnya ketika gue kembali mengadahkan kepala, gue liat Juan datang dengan gelagat seperti ingin mencari seseorang ke ruangan di dalam. Dia juga kemudian melihat kami berdua dan bersalaman setelahnya.
"Fay mana?" Tanya Juan tiba-tiba sembari bersalaman dengan Brian.
"Lah, udah cabut dari awal sama Gri." Ucap gue.
"Tadi ada Rofi juga." Tambah Brian setelahnya.
Selepas itu, Juan pergi menyisakan Brian dan gue yang masih bingung.
Sesekali, gue mencoba untuk beralih mengerjakan presentasi yang itu juga dibantu Brian untuk desainnya.
"Menurut lo gimana? Ditambah apa lagi? Gini kurang gak?" Tanya gue memastikan takut ada ketidaksesuaian atau kurang enak dipandang.
"Tambahin border deh tulisan yang itu, nah mantep. Slide yang udah oke menurut gue slide 3 sama slide 5." Tambahnya dan kembali berfokus pada laptopnya entah mengerjakan apa.
Tiba-tiba dia menambahkan peta Indonesia yang kontras warnanya dengan slide presentasi gue yang dominan abu-abu coklat. Peta tersebut berwarna dominan hijau-biru-merah.
"Ini peta apa?" Tanya gue bingung.
"Peta Indonesia kebalik" Jawabnya datar.
"Ngapain di taro sini? Gak nyambung" Ucap gue datar.
"Buat aksen aja" Jawabnya lagi.
"Kalau ditanya dosen penguji ini apa? Gue jawab apa?" Tanya gue lagi.
"Bilang aja peta Indonesia" Jawabnya dengan suara datarnya sembari tetap menatap pada layar laptopnya.
Gue gak mengerti arah pikirnya, jadi yaudahlah. Biarin aja Peta Indonesia itu di situ, lagian gak bakalan kelihatan banget.
Akhirnya, presentasi tersebut selesai. Draft selesai, presentasi selesai, tinggal ADKHI.
Allahu akbar!
Gue pusing banget.
Tapi kemudian gue baru sadar kalau gue mendapatkan bagian yang mudah sehingga selesailah semuanya, kecuali satu. Tanya jawab dan presentasi.
Akhirnya, gue mencoba mempresentasikan itu di depan Brian.
Lancar dan mudah saja. Sampai akhirnya sesi tanya jawab.
"Menurut saudara..." Ucapnya formal, bikin gue panik sendiri.
"Urgensi penelitian ini terletak pada... P-Pada adanya pengulangan pada sejarah... Perang... Kok? Ah bingung" Ucap gue terbata bata dan frustrasi sendiri.
"Tadi padahal tinggal dikit lagi loh, Pit. Nih kalau gue jawab pertanyaan gue sendiri ya..." Akhirnya Brian mencoba menjawab pertanyaannya sendiri.
Dia beneran kayak tutor gue.
"Bri, gue kayaknya gila deh. Gue gak sanggup." Ucap gue hampir menyerah sembari menyenderkan kepala gue di dinding sebelah kiri gue.
"Bisa. Ini baru gue loh yang tanya, gimana nanti sama dosen penguji?" Walau raut mukanya tidak menunjukan mimik meledek, tapi gue yakin dalam nada suaranya dia mencoba meledek gue walau ada secercah semangat yang ingin diberikan.
Gue akhirnya mencoba lagi, lagi, dan lagi.
Hingga akhirnya gue terbiasa walau ada satu kekhawatiran gue,
"Bentar, Bri. Gue takut kalau nanti ditanya soal konstruktivisme gimana ya?"
"Loh? Kenapa lo takut? Harusnya kan lo paling tau karena lo pakai teori itu dari awal. Coba gue tanya, apa yang lo tau soal konstruktivisme?"
Gue hanya menjawab dengan senyuman sembari mengangkat kedua alis gue, tanda bahwa gue mengerti padahal engga.
Si Brian juga melakukan hal yang sama. Dan dibalas dengan gue. Dibalas lagi dengan dia. Begitu seterusnya.
Kami seperti bersahut-sahutan menggunakan alis yang berujung membuat kami tertawa bersama.
Jam 10 malam, kami berdua pulang ke kost masing-masing.
Di kost, anxiety gue kambuh.
Gue udah terlalu panik bakalan di geprek di sidang nanti.
H-2 sidang alias hari senin. Gue kembali mengirimkan draft sur gue ke dosen penguji. Walau ada salah satu dosen penguji yang akhirnya gue temui h-1 di hari Selasa karena beliau meminta hard copy.
Di hari senin itu juga, gue kembali latihan sur dengan Dara di rumahnya. Entah kenapa gue bisa menjawab pertanyaan yang Dara berikan dengan lebih terarah dan mantap dibanding dengan gue sama Brian. Mungkin karena gak ada pressure apa-apa lagi sehingga pikiran gue sudah tidak kalut. Mungkin juga karena ada bantuan sokongan dari Ayam goreng Kalintang yang sebelumnya kami beli di depan kost Dara.
Pulangnya, gue langsung memikirkan pertanyaan yang mungkin ataupun celah dari tulisan gue. Sembari tentunya gue catat dalam buku gue. Hal itu dapat meredakan ketakutan gue walau gue berakhir kurang tidur.
Esok hari nya. H-1. Ini anomali.
Siangnya, gue ke kampus untuk memberikan draft sur gue ke dosen penguji yang sudah gue sempurnakan (walau gak sempurna).
Setelahnya, gue ngeprint lagi 5 buah draft di percetakan sebelah Sabar Subur (toko perabotan).
Gue akhirnya kembali laptopan di Tomoro. Untuk kembali memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar.
Ternyata sorenya hujan. Jam 3 di tengah hujan itu gue pulang ke rumah.
Entah kenapa, setelah gue menaruh laptop di kamar, gue malah ganti baju dengan celana pendek dan kaos lalu berjalan ke arah Jalan Sayang. Gue berhenti di Indomaret untuk membeli satu buah kamper. Gue juga gak tau buat apa, yang jelas gue kayak orang gak sadar. Setelah itu, masih dengan baju basah. Mungkin gue merasa kedinginan. Akhirnya, akal sehat gue memilih untuk berhenti di Bakso Pak Ari dan makan baksonya yang super jumbo itu walaupun gue udah makan 3 kali hari itu.
Aneh. Sumpah aneh. Gak biasanya gue kayak gini. Tapi, setelah gue bercerita beberapa hari setelahnya, ada yang bilang itu serangan panik. Memang gue panik banget, sih. Bukannya belajar, gue malah kayak orang gila malamnya.
Gak lupa, gue juga meminjam blazzer dari Sabriani. Hujan-hujan dia rela mengantarkan itu ke gue. Walau di tengah keanomalian itu, tiba-tiba Sabriani berkata di depan kost gue sembari mengeluarkan blazzer yang terlipat rapih dari dalam tas,
"Pit, tapi sorry ya, ini bukan blazzer mahal. Ini tipis"
Gue yang kala itu gak punya pikiran hanya bisa bilang,
"Iya gapapa"
Padahal, gue rasa gue bisa membalas dengan lebih proper. Tapi yang keluar dari mulut gue hanya itu untuk mengimbangi Sabriani yang kalau ngomong cepetpun, gue gak bisa.
Hari itu, gue sudah membatin dalam hati.
"Besok hari kematian gue."
Sadar bahwa kegilaan itu tidak boleh terus berlanjut, akhirnya gue karaokean lagu arab.
Kan.
Sumpah, gak jelas.
Wianda di grup sudah memperingatkan gue,
"Tidur, Pit. Jangan kurang tidur."
Yang hanya gue iyakan walau nyatanya memejamkan mata hanya membuat gue makin panik. Maka, gue mencoba mengatur ritme napas dan barulah gue bisa tertidur dengan tenang.
Hari H.
Entah kenapa gue terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda dengan kemarin.
Gue tau gue bakalan mampus, tapi ya udah.
Gue tau gue gak siap, tapi ya mau gimana lagi?
Nasi sudah menjadi jadi.
Gue gak bisa mundur atau minjem mesin waktu Doraemon buat pergi ke Negeri Matahari.
Entah kenapa, pagi itu gue malah teringat quotes dari Little Prince,
"People have forgotten this truth", the fox said. "But you musn't forget it. You become responsible forever for what you've tamed. You're responsible for your rose."
Apa yang telah kita mulai, harus kita selesaikan dengan tanggung jawab.
Akhirnya gue berangkat pukul 8 pagi ke prodi. Di sana gue bertemu dengan kating angkatan 20 yang baru mau sur juga. Kami mengobrol singkat sampai akhirnya dibuka juga sidang oleh kaprodi.
Waktu gue tinggal menghitung menit.
Sampai akhirnya, tibalah giliran gue.
Sebelum masuk, salah satu dosen penguji berkata,
"Teh Anggi (dosen pembimbing) sama Ipit suka tantangan"
Gue akhirnya presentasi walau dengan gugup dan terbata-bata karena banyak mahasiswa alias teman-teman gue yang menonton tepat di depan gue. Gue nervous.
Hingga sampailah pada sesi tanya jawab.
DUAR DUAR DUAR!
Ekspektasi dan gambaran gue sebelumnya gak banyak melenceng. Jelas gue terbantai. Walau dibayangan gue lebih buruk, tapi yang ini juga gak kalah buruknya.
Selesainya, teman-teman gue berkata bahwa mereka juga belajar banyak dari skripsi gue.
Entah apa yang mereka pelajari, hanya saja di hari itu, gue merasa bahwa gue lah makhluk paling tolol sejagat.
Satu hal yang paling membekas di gue waktu salah satu dosen penguji selepas sidang berkata,
"Saya tau kamu suka baca buku, tapi bukan berarti kamu harus maksain apa yang kamu suka di penelitian"
DUAR! Kiamat ini kiamat!
Walau akhirnya diperhalus dengan,
"Maksudnya bagus kalau kamu suka baca, tapi kamu bisa nulis soal bacaan kamu di platform lain tapi bukan di skripsi"
Tetap saja. Gue sakit hati. Tapi yang jelas, gue gak pernah menanamkan kebencian apapun pada mereka.
Dunia serasa tidak berpihak pada gue.
Ditambah dengan teman-teman gue yang tau kalau gue suka sekali baca buku datang jauh-jauh memberikan hadiah buku, padahal saat itu gue sedang eneg-enegnya liat buku ataupun tulisan.
Bahkan, gue sempat membeli buku dan meminta hadiah buku ke orang tua gue untuk hadiah sur. Walau naas, sampai sekarang belum juga gue baca tuntas.
Sebetulnya, gue gak enak nulis ini.
Gue bukan gak menghargai pemberian teman-teman dan orang tua gue. Justru, gue sangat apresiasi dan senang sebenarnya karena mereka adalah orang-orang yang mengenal gue sangat dalam, cuma masalahnya waktunya tidak tepat aja.
Maka, gue menyimpan buku-buku tersebut dengan rapih di kamar kost gue sampai sekarang. Takut-takut nafsu membaca gue kembali lagi karena di hari itu sampai beberapa hari kemudian, gue jadi reading slump alias kehilangan minat atau semangat membaca secara tiba-tiba. Kegiatan membaca sekarang jadi beban berat untuk gue.
Hari itu bukan hari yang menyenangkan untuk gue. Tapi, gue mencoba sebisa mungkin menutupinya karena teman gue, Rahma, juga sedang sur dan gue juga senang karenanya.
Pulangnya, kami makan di Elok setelah sesi foto-foto yang menguras tenaga.
Lalu kami berencana nonton Now You See Me di bioskop.
Film ini adalah salah satu yang paling gue tunggu sejak tahun kemarin. Gimana engga? Trik sulap yang megah membuat rahang gue ternganga sewaktu menontonnya.
Tapi, di tengah bioskop, gue malah menangis lagi. Teman-teman gue taunya gue tidur, jadi tangis gue tak tampak dan gue mencoba untuk tidak terbawa suasana sedih dan mengikuti arah pembicaraan mereka setelahnya.
Teman-teman gue berencana menginap di rumah Thya. Gue memilih untuk tidak.
Gue rasa, ada yang harus gue selesaikan di malam itu.
Esoknya, kamar gue berantakannya bukan main. Sejujurnya, gue bukan orang yang senang melihat kamar berantakan. Tapi hari itu, gue ga bisa untuk bangkit dari kasur sama sekali. Kegiatan gue seharian adalah menangis, capek, tidur, bangun, nangis lagi, capek, tidur. Gitu aja terus.
Hal itu terjadi selama beberapa hari.
Walau ada saat di mana gue keluar, tapi saat-saat itu hanya memakan waktu beberapa jam saja. Sisanya gue pulang dan melakukan kegiatan tangis tanpa henti dan tidur kalau udah capek sendiri.
Mungkin kedengarannya lebay, tapi apa yang gue tangisi bukan sur gue, melainkan hilangnya diri gue saat itu.
Biasanya, gue yang selalu bangun pagi dan baca buku atau melakukan hal-hal menyenangkan, pagi itu semuanya berubah total.
Gue merasa bahwa ini bukan diri gue. Ke mana gue yang produktif dan ceria setiap paginya? Ke mana rasa penasaran yang selalu muncul setiap harinya?
Ini rasanya aneh. Apalagi saat gue menelpon dan bercerita dengan nyokap, dia gak bisa bohong kalau dia juga merasakan sedih seperti apa yang gue rasa. Tapi, dari sudut bibirnya, dia selalu memberikan pesan semangat kepada gue,
"Mama gak pernah gak bangga sama Ipit. Ipit gak pernah ngerepotin mama, justru dari Ipit, mama banyak belajar jadi orang tua. Ipit itu perempuan terkuat yang pernah mama kenal. Jangan nangis terus ya, Sayang."
Kalimat sakti yang kemudian mampu membuat mata gue bengkak. Gak cuma itu, tiba-tiba timbul semangat baru dalam diri gue.
Gue kemudian membangun habit baru.
Gue tetap bangun pagi.
Uninstall Tiktok.
Dan buka Youtube setiap hari buat dengerin podcast entah apapun itu.
Di bantu dengan teman-teman gue yang siap datang untuk mendengarkan curahan hati atas meninggalnya gue yang lama, gue semakin bangkit. Tapi, gue tetap merasa ada yang hilang.
Baca buku.
Entah kapan gue kembali memulai kebiasaan baca buku, tapi yang gue ingat, ketika sehabis nangis, gue mencoba untuk mengambil buku As Long As The Lemon Trees Grow karya Zoulfa Katouh yang berada di sebelah meja gue. Ajaibnya, buku ini beneran page turner banget. Itulah buku pertama yang gue baca setelah sur dan menyelamatkan gue dari reading slump.
Intinya, gue sudah kembali mencoba pulih. Sadar bahwa dunia tetap berjalan sebagaimana mestinya, gue mencoba untuk tetap hidup. Gue mencoba mencari arti hidup di umur gue yang sedikit lagi menginjak 22 tahun ini. Lalu lagu Rasukma yang berjudul Yang Berlalu Biar Berlalu kembali mengalun mesra di telinga.
Yang berlalu biar berlalu
Apa enaknya dibalut sendu?
Yang berlalu biarlah terasa kelu
Orang bilang tangis membantu,
itu tak selalu.
Sadar bahwa belum sepenuhnya pulih, gue merasa bahwa gue harus menyendiri.
"Gue harus ke Jogjakarta. Kalau aja gue balik masih murung, gue gak tau lagi harus apa..." Ucap gue pada diri sendiri dengan nada pasrah.
Dan di sinilah gue. Di Jogjakarta, di tempat antah berantah.
Jogjakarta, 27 November 2025
Dokumentasi Seminar Usulan Riset 12 November 2025




.jpeg)




.jpeg)



.jpeg)


















.jpg)
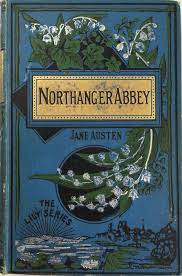

Komentar
Posting Komentar