adiós amigos
Halo!
Gue menulis blog ini sebenarnya dari 17 Juli 2022, sampai sekarang di tanggal 19 Agustus, gue masih dalam proses mencerna kembali apa yang telah gue lakukan dalam waktu sebulanan ini. Mungkin ketika lo lagi baca blog ini sekarang, gue sedang dalam perjalanan menuju Jatinangor. Tempat yang akan menampung salah satu warga Jakarta yang aneh ini untuk tinggal selama empat tahun disana. Penting bagi gue untuk berpamitan pada orang-orang di luar sana khususnya orang terdekat gue yang entah sudah berapa lama menemani gue selama gue di Jakarta. Karena ga mungkin kalau gue ngetok pintu satu persatu ke rumah orang-orang itu, jadi ini adalah salah satu tulisan yang gue buat khusus untuk orang-orang itu. Iya, kalian.
Sudah delapan belas tahun gue hidup di Jakarta. Walau lahir di tanah sunda juga yaitu di Kota Serang, tapi Jakartalah yang membesarkan gue setelah satu minggu gue lahir. Jakarta yang mengajarkan gue bahwa kehidupan disini sekeras batu kali. Jakarta juga yang membawa gue memasuki gerbang dalam dunia pendidikan yang mungkin kalau gue hidup di tanah lain selain Jakarta, gue akan berpikir bahwa pendidikan ga sepenting itu. Atau mungkin paling parahnya gue bakalan mikir "Nikah seru kali ya?"
Untungnya, gue hidup di Jakarta.
Yah, walaupun kata orang Jakarta padat penduduk, Jakarta macet, Jakarta penuh polusi, tapi Jakarta adalah cinta pertama gue. Kota yang katanya tidak layak untuk ditinggali, tapi memiliki makna sendiri. Iya, se-gak-rela itu gue meninggalkan Jakarta.
Hujan bulan Juli di Jakarta menjadi saksi bisu kegalauan gue untuk pergi. Waktu itu, gue jalan dengan teman gue pergi ke Perpustakaan Cikini di daerah Jakarta Pusat. Sembari mendengarkan teman gue yang sibuk berceloteh ria, tiba-tiba gue berfokus pada pemandangan kota melalui jendela bus transjakarta. Mata gue sibuk menjelajah kota Jakarta yang saat itu terlihat asri dan antik (Jakpus ya, Jaktim diam dulu) sedangkan pikiran gue sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan konyol seperti,
"Haruskah gue pergi?"
Sembari menimbang-nimbang itu, gue kembali memandang teman gue sambil sedikit demi sedikit merespon apa yang dia katakan. Lalu pikiran gue kembali bertanya,
"Seberapa besar perubahan yang akan terjadi dalam hidup gue ketika gue pergi? Apakah gue dan dia masih bisa berteman setelah sekian lama ga ketemu?"
Iya gue paham, seberapa besarpun perubahan gak akan berefek banyak pada dunia ini karena gue bukan main character kayak di anime. Tapi, hal itu pasti akan berpengaruh pada hidup gue sendiri.
Selain meninggalkan suatu tempat yang nyaman, gue juga harus meninggalkan orang-orang yang membuat gue nyaman untuk tinggal di suatu tempat bernama Jakarta ini.
Jujur, gue gak bermaksud untuk mendramatisasi kepergian gue atau membuat kalian semua mewek (lagian males juga). Gue ingin memberikan pandangan gue sendiri tentang apa itu pergi.
Sekali waktu saat gue pergi ke Kota Tua bersama dengan satu teman gue. Menurut gue, kepergian kami ya seru-seru aja. Ketawa, becanda, dan foto-foto, satu per satu kami abadikan dengan perasaan senang dan bahagia (gatau sih dia). Kami juga kembali dengan perasaan bahagia yang tersisa.
Sama juga waktu gue dibawa pergi oleh teman gue mengikuti kemana arah takdir membawa, katanya. Jujur, gue agak ketar-ketir karena harus mengikuti takdir entah berantah yang membawa kami berlima dari Jakarta Utara ke Cibubur lalu ke Condet lalu balik lagi ke Ciracas.
"Ini trip spesial buat lu, Pit" Kata si pengendali takdir.
Padahal yang pergi duluan dia. Gue hanya mencoba mengiyakan sambil kembali menikmati trip spesial yang disediakan. Ditambah dengan keteledoran salah seorang teman gue yang nitipin motor dalam kondisi masih nyala tapi kuncinya dia bawa. Gimana gue bisa nikmatin trip spesial ini?
Tapi anehnya bisa. Walau ada tambahan penumpang dari Condet, gue masih bisa menikmati Jakarta sore itu. Jakarta yang menyatukan takdir sial kita malam itu. Takdir yang membawa kita pergi ke rumah masing-masing dan entah kenapa gue masih merasa bahagia karena perginya kita ke rumah masing-masing (Seneng karena pinggang ga lagi encok)
1...
3...
4...
5...
9...
Satu persatu dari mereka pergi. Sehingga gue mengerti apa esensi dari pergi yang sesungguhnya. Kali itu mungkin gue terlihat senang dan baik-baik aja. Emang gue baik-baik aja, tapi gue gak senang. Setelah sadar bahwa teman-teman gue pergi, barulah gue sadar bahwa kepergian gue juga sudah dekat.
Entah berapa kali, entah juga berapa hari, semua kegiatan gue lakukan di luar. Nyokap gue boleh berbangga bahwa anaknya gak pernah main ke luar dan jauh dari pergaulan bebas. Tapi jujur, gue merasa bahwa kebebasan ini baru gue dapatkan ketika gue berada di umur sekarang-sekarang ini. Rasanya seperti gue baru lahir ke dunia dan merasakan hal baru tapi kemudian gue harus pergi secepat mungkin. Rasanya seperti baru kemarin.
Lucunya juga saat gue harus pergi ke tempat yang akan gue tuju. Bandung, ralat, Jatinangor.
Di Bandung sendiri, gue akui. Gue jatuh hati. Kala itu Bandung sedang hujan rintik. Gak sederas hujan di Jakarta, gak sekering juga hujan di NTT (Riset dari pelajaran geografi)
Hujan di Bandung seakan pas untuk turun. Nama-nama jalan yang selama ini hanya bisa gue dengar dari podcast, lagu, video maupun gue baca melalui buku-buku bacaan, akhirnya, gue bisa menginjakan kaki di sini. Sembari menyambut kepergian gue yang sebentar lagi akan tiba, gue seakan-akan mempelajari bagaimana caranya untuk bertahan hidup di sebuah tempat baru. Tempat yang gak akan bisa gue bandingkan dengan kota dimana gue tinggal maupun lahir. Bandung dan Jatinangor seperti punya tempat sendiri.
Di hari yang sama, gue memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Sebuah penyesalan dimana gue gak berani nambah lauk dan nasi di Warteg Simpang Dago karena jam yang seakan memanggil gue untuk kembali. Malam itu, gue berpikir lagi,
"Lalu, apa esensi dari kembali?"
Sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini seperti sebuah pertanyaan retoris bagi gue.
Bahkan, hal itu gak gue dapat saat gue pulang ke rumah dari perpustakaan di daerah Cikini.
Saat dalam perjalanan pulang ke rumah dari perpustakaan, gue selalu memperhatikan jalan. Sembari ditemani hujan rintik dan semakin lama semakin deras, ditambah dengan suara musik yang saat itu tengah memutar lagu Changes nya Jeff Bernat sukses membuat gue galau akut. Otak gue sibuk memproduksi pertanyaan-pertanyaan gak masuk akal kayak,
"Nanti disana, gue bakalan bisa sebahagia kayak disini ga ya?"
Sampai-sampai gue hampir muntah karenanya. Makanya waktu di Halte SMK 57 Jakarta Selatan, gue turun saking gak kuatnya sama apa yang gue pikirin sendiri. Overthinking yang gak habis-habis itu bahkan berlanjut sampai keesokan harinya. Saat itu masih hujan deras. Gue buru-buru memesan grab. Rumah gue kira-kira 4,8 Kilometer dari sana. Sedangkan teman gue bertanya,
"Buku lu gimana, Pit? Lu kan bawa buku"
"Gue gak peduli deh, yang penting cepet pulang"
Untung abang grabnya bawa jas hujan. Tas berisikan buku itu ditaruhnya di jok motor sehingga novel Sang Alkemis gue masih utuh dan gak kena air setetespun.
Sebelumnya sih, gue gak terlalu mikirin tentang gue yang akan tinggal jauh dan hanya sesekali bisa balik ke Jakarta. Bahkan, teman SMP gue yang malah mikirin,
"Kira-kira kita masih bakal temenan ga ya kalau pada ngerantau?"
Jujur, saat itu gue merasa itu adalah pertanyaan terkonyol yang pernah gue denger. Lagian, apa jarak bisa membatasi sebuah hubungan? Kalau dulu mungkin iya. Merpati gak mungkin kuat terbang jauh nyebrang pulau apalagi negara. Tapi sekarang kan ada teknologi namanya google meet, skype, zoom, bahkan ome tv pun hadir menemani hari-hari gabut kalian sembari bisa dapet teman dari berbagai negara. Easy bukan?
Gue saking capeknya dengan teman gue membalas dengan,
"Ya masih lah Cok, kan gak beda alam 😭"
Kalo beda alam bisa mainpun, 100% gue jamin, temen gue gak bakalan mau temenan lagi sama gue.
"Kan maksudnya siapa tau pada bener-bener sibuk sama dunia barunya"
Saat itu, belum terpikir oleh gue tentang 'sibuk sama dunia baru' yang dia maksud. Pikiran gue hanya mengatakan bahwa berteman bisa dilakukan darimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tapi setelah kelebihan pikiran kemarin, gue baru merasakan bahwa hubungan apapun itu dalam jarak yang jauh tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin juga gue kebanyakan dengerin lagu Raisa-LDR, tapi gak menutup kemungkinan hal itu juga berdampak dalam pertemanan.
Teman gue yang lain malah bilang,
"Nyesel kan lu, gak ikut SIMAK UI?"
Tapi setelah gue pikir, bukannya nyesel, gue malah jujur aja seneng juga.
Ngerti gak sih lu?
Di satu sisi gue berat untuk meninggalkan kota ini, di sisi lain gue juga ingin pergi.
Saat itu gue hanya berkilah,
"Engga juga, karena UI bukan tujuan gue, pun seandainya gue diterima juga, belum tentu gue akan ambil. Bahkan kemungkinan besar gak akan gue ambil karena jurusannya gak sesuai dengan apa yang gue mau."
Jujur aja waktu daftar SIMAK gue merasa rendah diri, makanya gue gak menaruh Hubungan Internasional waktu pendaftaran.
Maka saat itu gue berpikir.
"Apa memang Jatinangor adalah tempat terbaik untuk gue? Apa ada hal seru yang menunggu gue sehingga gue diharuskan untuk setidaknya mencoba selama empat tahun untuk tinggal disana?"
Entahlah.
Kalo kata The Panasdalam sih "Sudah jangan ke Jatinangor"
Tapi pikiran gue berkata bahwa gue harus.
Yah, mungkin memang berat. Untuk meninggalkan apa yang gue punya di rumah. Keluarga, teman-teman, buku-buku yang sengaja gue tinggalkan di rumah, Jojo alias kucing gue, jalanan lenggang di malam hari, jalan raya yang padat karena hari senin banyak anak sekolah di jalanan, kenalpot angkot yang hitam kayak minyak di tenda pecel lele, bahkan musim hujan di Jakarta terlalu sayang untuk gue tinggal.
Gue dengan rendah hati ingin berterima kasih pada apa yang telah terjadi selama delapan belas tahun ini. Pada hal-hal yang telah menemani gue selama gue tinggal di Jakarta. Hal-hal yang entah baik atau buruk dengan mudah gue telan padahal hal itu termasuk hal yang gak mudah untuk gue lewati. Pada orang-orang yang selalu mendukung gue untuk mencapai dan mengajari gue bagaimana caranya untuk bermimpi. Tentunya juga pada hal-hal di luar nalar yang sukar dimengerti selama gue tinggal di Jakarta ini.
Besar rasa terima kasih yang ingin gue curahkan pada kalian.
Jadi, keputusan final gue adalah pergi.
Jakarta memang terlalu indah untuk gue lupa, tapi Jatinangor juga menarik untuk dicoba.
Selamat tinggal untuk sementara~








.jpg)
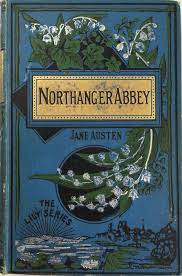

Komentar
Posting Komentar